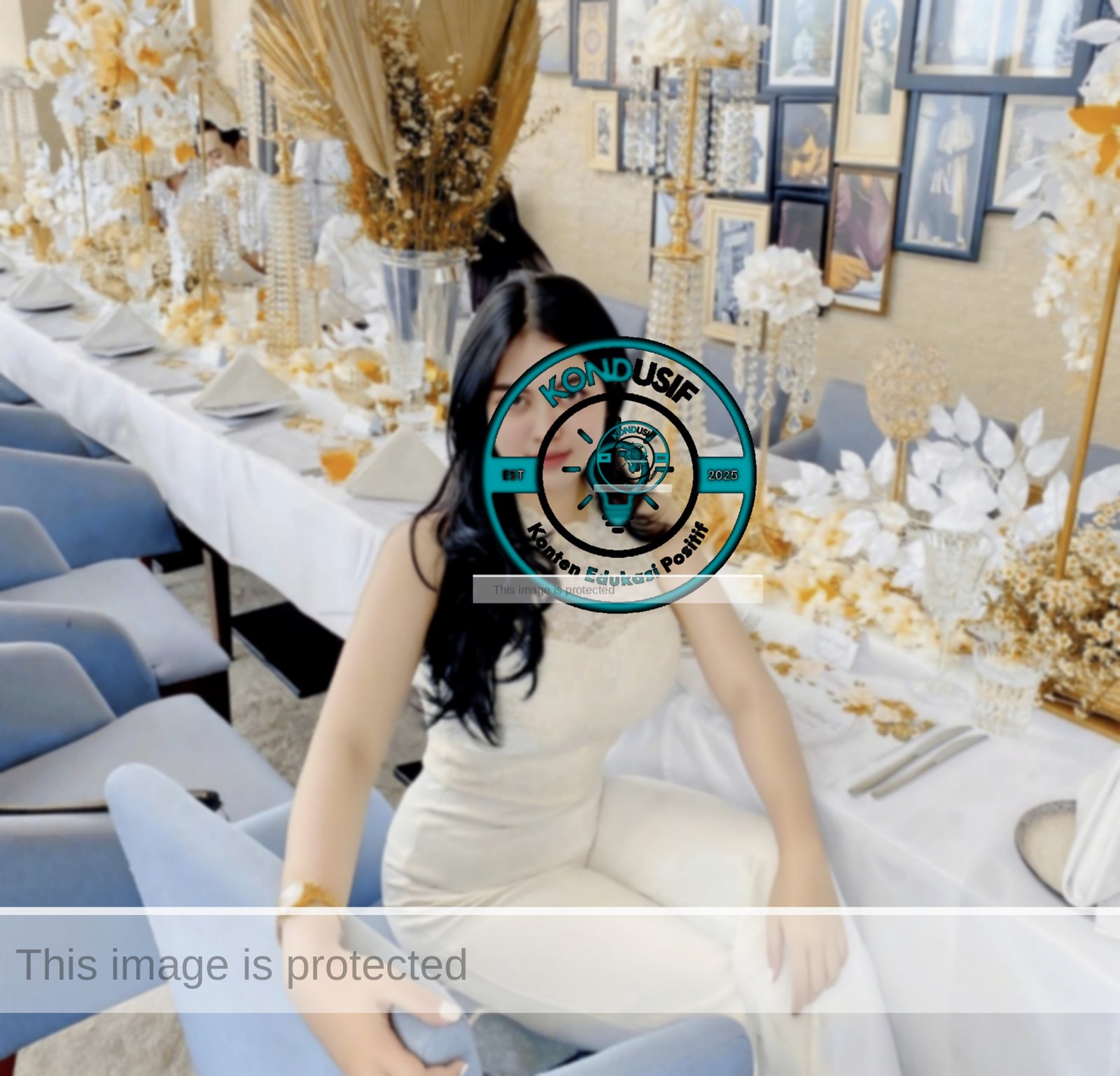Opini, Kondusif.com,- Ada satu hari dalam setahun yang selalu membuat dadaku terasa sesak Hari Ayah Nasional.
Orang-orang sibuk mengunggah foto bersama ayah mereka, menulis caption penuh cinta, menceritakan betapa berartinya sosok itu dalam hidup mereka. Dan aku… hanya bisa diam.
Bukan karena aku tidak ingin ikut bahagia, tapi karena aku sudah tidak punya ayah untuk kupeluk, untuk kutatap, atau sekadar untuk kuucapkan, “Selamat Hari Ayah.”
Ayah Pergi Terlalu Cepat
Aku kehilangan ayah saat masih SMP. Saat itu, aku bahkan belum paham apa arti kehilangan. Semua terasa kabur.
Rumah jadi sepi, pagi kehilangan aroma kopi, dan senja terasa lebih dingin dari biasanya.
Dulu, setiap pagi, beliau suka bersiul kecil sambil menyeduh kopi hitamnya.
Sekarang, suara itu hanya tinggal di kepalaku, samar tapi hangat.
Kadang, saat pagi datang dan aroma kopi menyelinap dari dapur tetangga, aku berhenti sejenak mencoba mengingat, rasanya punya ayah yang menatapmu dengan bangga.
Aku kangen momen sederhana seperti itu. Kangen cara ayah memanggilku, “Neng, jangan lupa sarapan.”
Kalimat yang dulu kuanggap biasa, kini terasa seperti doa paling berharga yang pernah aku dengar.
Hari Ayah Nasional Hari yang Paling Sepi
Buat banyak orang, Hari Ayah adalah momen merayakan. Tapi buatku, ini hari paling sunyi.
Aku tidak menyiapkan kue, tidak menulis ucapan di kartu, tidak memeluk siapa pun. Yang kulakukan hanya menatap langit dan berbisik pelan, “Apa Ayah dengar?”
Kadang aku merasa bodoh karena masih berharap bisa bicara dengannya.
Tapi kehilangan orang tua tidak ada tamatnya. Waktu hanya membuat luka itu lebih bisa ditahan, bukan hilang.
Ada hari-hari di mana aku bisa tertawa seolah semuanya baik-baik saja.